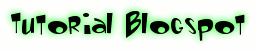Saya telanjang di depan kaca, meraba payudara saya, menelusuri pinggul yang replika biola, melirik cekungan di antara paha.
Saya masih telanjang, di depan kaca, mata saya berkaca-kaca.
***
Ternyata, menjadi perempuan itu begitu menyakitkan. Mungkin itu sebabnya begitu banyak perempuan yang gemar menangis. Saya juga ingin bisa menangis seperti mereka ketika tetangga saya yang perjaka tua itu kerap mempermainkan jemarinya di antara paha saya. Tapi waktu itu saya masih begitu kecil sehingga ketakutan menghambat kelenjar air mata yang seharusnya keluar.
Saya juga ingin menangis saat ayah tiri saya, lelaki berperut dengan gelambir, kerap datang ke kamar saya ketika Ende tidak ada di rumah. Jemarinya yang kapalan dan berminyak itu merayapi payudara saya. Sambil mengerutkan kening dan wajah kesal, ia juga memaki kenapa payudara saya tidak sebesar kakak perempuan saya, agar ia bisa lebih leluasa bermain di sana. Itu katanya. Tapi lagi-lagi saya tidak bisa menangis karena dia mengancam akan membunuh saya. Lagipula, waktu itu saya masih remaja, belum mengerti apa-apa.
Menjadi perempuan memang menyakitkan. Kakak perempuan saya itu buktinya. Ia terkapar di lantai bersimbah darah dengan bekas lebam di sekujur badan. Ia merintih, memohon, meracau, bahkan mencium kaki ayah tiri kami, tapi pukulan demi pukulan tetap dihadiahkan tangan-tangan setan.
Ende, yang waktu itu tengah mengandung memapah saya ke kamar dan menceritakan hal-hal yang nyaris membuat saya muntah.
“Kakakmu Florita itu berbuat lacur, Ervina. Lihat itu, perutnya mengembung tak karuan dan ia tak mau memberi tahu siapa laki-laki yang telah menggagahinya. Ah, Ervina. Kakakmu Florita itu pantas dipukuli supaya ia mengaku.”
Saya ingin sekali berteriak di telinga Ende bahwa ayah dari bayi yang tengah dikandung oleh Florita adalah suaminya sendiri, ayah tiri kami. Tapi bajingan itu akan membunuh kami berdua; saya dan Florita. Mungkin juga akan membunuh kami berempat lalu membuang mayat kami ke kebun jagung. Maka saya diam, tak berani berbicara.
Lagi-lagi, kakak perempuan saya Florita meringkuk di ranjang saya dengan luka menganga. Di sekujur tubuh, terlebih lagi di kedalaman dadanya. Ia menangis. Suaranya tercekat karena takut didengar oleh Ende dan ayah tiri kami yang tengah berada di luar. Saya ingin menangis juga untuknya, tapi kelenjar air mata saya kerap berkhianat, tersendat. Maka saya hanya bisa memeluk Florita erat sementara mulut saya tetap terkatup rapat.
“Untung saja payudaramu rata, Ervina,” bisik Florita di sela tangisnya. Kalau saja payudaramu ranum seperti punyaku, keparat itu tentu akan menggagahimu pula.”
Saya meraba dada saya, sepersekian detik merasa beruntung. “Kau masih sakit?” saya meraba lebam di pipi Florita.
Ia diam saja.
“Ayo kita pergi dari sini, Kak…” suara saya dibuat pelan.
“Ema pasti akan mengejar kita, Ervina. Kau pikir dia rela dua orang anak gadisnya lari?” mata Florita berkaca, ketakutan.
“Jangan panggil laki-laki busuk itu dengan sebutan Ema! Ema kita sudah mati, ingat?” kepala saya membayang wajah Ema, ayah kami tercinta yang pasti merelakan nyawanya agar kedua putrinya tidak harus terperosok lubang neraka.
Florita diam.
“Bangka Ajang ini terkutuk. Aku ingin pergi merantau, meninggalkan tempat ini,” gigi saya gemeletuk.
“Pergilah Ervina, aku tetap di sini. Tidakkah kau lihat perutku sudah sebesar karung yang mengembung?” ia mengelus perutnya, payudaranya menyembul. Payudara yang tidak rata seperti punya saya.
* *
Menjadi perempuan memang menyakitkan. Lebih menyakitkan ketika seharusnya saya menangis tapi tak bisa menangis. Bahkan ketika mendapati kabar bahwa kakak perempuan saya Florita bunuh diri di kebun jagung setelah membunuh bayinya sendiri. Bayi yang seharusnya tidak ia miliki. Bayi yang menjadi bukti kebiadaban lelaki.
“Aku mencintaimu, Ervina. Kau adalah perempuan yang segalanya aku inginkan,” Laba mendekatkan bibirnya ke telinga saya. Mulutnya menguarkan asmara, begitu pula jemarinya; mulai liar meraba-raba.
Saya tidak bangga. Saya tidak merasa menjadi primadona. Karena mungkin saya tidak pernah mencintai Laba, bukan karena dia tidak tampan, bukan karena dia tidak mapan. Tapi karena dia laki-laki.
“Aku akan membuat hidupmu bahagia. Kamu tak usah kembali ke Bangka Ajang, desa yang kau sebut terkutuk itu. Tinggal lah di sini, di rumah ini,” bisik Laba lagi.
Saya tidak pintar, tidak berpendidikan bagus, tapi saya mampu keluar dan pergi jauh ke seberang pulau. Saya bisa bertahan dari guncangan macam apapun. Terbukti, saya masih bisa makan walau merantau di Batam sendirian. Keberadaan Laba sebagai lelaki kaya yang selalu ingin menaklukkan setiap perempuan yang ia temui sedikit banyak menguntungkan. Secara finansial, ia mampu menyokong hidup saya. Tapi saya bosan diperbudak laki-laki; jadi bulan-bulanan.
Tangan Laba kian liar. Jemarinya bergetar, dada saya berdebar-debar. Bukan karena terangsang tapi justru ingin tangan Laba segera hengkang. Hengkang dari payudara saya, dari selangkangan saya.
* *
Menjadi perempuan memang menyakitkan. Lebih menyakitkan ketika seharusnya saya menangis tapi tak bisa menangis. Lebih menyakitkan lagi ketika malam pertama saya dengan Laba menjadi sebuah prahara. Bukan hanya karena payudara saya yang rata. Bukan hanya karena saya menikah dengan Laba, lelaki yang tidak pernah saya cinta. Melainkan karena cekungan di antara paha yang dulu saya sangka vagina itu tidak sempurna.
“Penipu!” tamparan Laba mendarat di pipi saya, bibir saya berdarah, pipi saya memerah.
Saya tak mampu bersuara, saya tak tahu harus berkata apa.
“Kau perempuan jejadian, Ervina! Aku menyesal menikahimu. Kau penipu,” Laba masih menandak-nandak dalam amarah sementara saya masih tak mampu berkata apa-apa.
Saya masih mengira ini hanya persoalan payudara saya yang rata.
“Dulu kukira payudaramu yang rata itu bukanlah apa-apa, tapi ternyata vaginamu itu palsu. Mana mungkin ada perempuan yang memiliki buah zakar? Kau kira aku ini lelaki penyuka sesama jenis? Cih, penipu licik!” Laba meludahi saya, kental dan berbau bacin.
Saya meraba payudara saya yang rata, kemudian menelusuri celah di antara paha yang saya kira adalah vagina. Jemari saya meraba benda yang selama ini tidak pernah saya akui ada. Dua buah zakar bergelantung murung. Pungung saya melengkung, meraba-raba perih dan pedih.
“Kau bukan perempuan, Ervina! Bukan!” amarah Laba bertambah-tambah.
Memang, ternyata ini bukan hanya persoalan payudara saya yang rata.
* *
Menjadi perempuan itu menyakitkan. Masih menyakitkan ketika Laba yang konon mencintai saya hingga sanggup menyerahkan dunia dan seisinya ke hamparan tangan saya itu segera menggugat cerai di hari pertama pernikahan. Segera, saya dicaci sebagai penipu, mahluk tak tahu diri yang ingin menang sendiri. Tapi, saya merasa bebas, meski hati saya kebas. Toh, saya tak pernah mencintai Laba. Dan saya bukan perempuan seperti selama ini saya kira.
* *
Saya telanjang di depan kaca, meraba payudara saya yang rata, menelusuri pinggul yang replika biola, melirik cekungan di antara paha yang saya sangka adalah vagina.
Saya masih telanjang, di depan kaca, tertawa hingga mata saya berkaca-kaca.